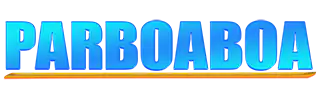PARBOABOA, Pematangsiantar – Kelompok musik terkemuka Pematangsiantar, Punxgoaran, sempat mendapat mobil Hiace dari Pemkot untuk tur mereka, pada satu masa. Tapi itu hanya di akhir masa jabatan walikota. Setelahnya, kembali ke titik nol.
Lalu, Guido Hutagalung, sang vokalis, pernah menyarankan pembangunan ampiteater dan studio musik-kafe untuk dimanfaatkan komunitas musisi setempat. Tapi, lontaran gagasan ke otoritas kota itu kemudian laksana debu yang dienyahkan entah ke mana oleh angin bertiup.
Mandiri! Itu menjadi pilihan kalau mau tetap eksis. Menunggu sampai ekosistem yang baik terbangun itu bisa sia-sia. Begitulah, Punxgoaran dan Siantar Rap Foundation (SRF) praktis jalan sendiri selama ini. Juga, kelompok metal Paku Mati.
Punxgoaran, SRF, dan Paku Mati menolak menjadi band yang hanya mengikuti selera pasar. Seperti kata Guido, kalau nggak punya benang merah, nggak akan ke mana-mana. Ia menyayangkan banyak band lokal yang hanya mengandalkan lagu pihak lain (cover) karena tanpa keberanian mencipta.
“Band tidak bikin kaya. Tapi dari situ kita ketemu orang-orang yang memperkaya cara pandang,” tutur Guido Hutagalung.
Guido menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan musisi cover tampil di acara ulang tahun kota, asalkan dana dari pemerintah dialihkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kontras dengan Alfred dari SRF yang menyatakan lebih menghargai karya orisinal meski buruk daripada hanya menyanyikan lagu orang.

Paku Mati tetap idealis. Mereka menolak menjadi band yang mengejar uang atau popularitas. “Kalau kami niat cari duit, band ini sudah bubar dari dulu,” kata seorang awaknya.
Lagu mereka adalah ekspresi jujur, bukan komoditas. Mereka melihat bahwa semakin tua usia band metal, justru semakin dihormati.
Memasukkan warna etnik Simalungun dalam musiknya, Paku Mati pernah sepanggung dengan raksasa asal Brazil, Sepultura, di Medan pada 9 Desember 2017. Mereka ini mekar di kala atmosfir musik metal Siantar masih sehat betul.
Masa kejayaan musik cadas ini di sana pada periode akhir 1990-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu, Siantar Corpse Grinder (SCG) hadir sebagai komunitas metal pertama Siantar. Underground Community (SUC) muncul kemudian. Kegiatan pun macam-macam. Juga, ajang. Siantar Metal Fest dan Extreme Fest yang terkemuka. Siantar Metal Fest yang paling semarak adalah yang di tahun 2011. Saat itu tampil juga kelompok-kelompok asal luar kota selain Paku Mati dan para sejawat mereka asal Siantar.
Masa gemilang itu sudah lama lampau. Begitupun, Paku Mati belum mati. Kendati sudah tak belia lagi, mereka tetap berkreasi. Memang, terkadang harus memproduksi lagu setahun lamanya di studio sendiri yang terletak di Serbelawan, kota di pinggiran Pematangsiantar. Regenerasi menjadi masalah bagi mereka, kini.
"Usia kami sudah cukup untuk main di panggung saja, bukan untuk turun tangan lagi ke lapangan. Tapi, kalau bukan kami, siapa lagi?" kata seorang dari mereka.
Karakter vs Pasar
Bloodnesia tetap percaya bahwa karakter jauh lebih penting ketimbang mengikuti arah pasar. Mereka tidak membentuk musik untuk menyesuaikan diri dengan selera dominan, melainkan menjaga jalur yang telah mereka pilih sejak awal keras, reflektif, dan tak kompromistis.
Band metal macam Bloodnesia tetap percaya pada etos kerja: no compromise. Mereka tidak menjilat sponsor, tidak merayu pejabat, tidak mengejar panggung seremonial. Tapi justru karena itu, ruang mereka makin sempit. Panggung mereka terbatas, media tak melirik, dan penggemar makin menua.
Kesenjangan ini bukan soal kualitas, tapi soal akses. Musik yang menggabungkan budaya lokal dengan genre populer lebih cepat naik karena terasa familiar dan representatif. Tapi itu bukan berarti musik metal tak layak naik. Mereka hanya belum diberi panggung yang adil.
Di kota seperti Pematangsiantar, suara yang keras sering dianggap ancaman. Tapi suara keras tidak selalu berarti brutal. Kadang, itu justru suara yang paling jujur. Jika kota ini ingin hidup secara kultural, maka bukan hanya suara yang manis yang harus dirayakan, tapi juga suara yang keras, tajam, dan berani. Karena dari sanalah, kejujuran paling dalam berasal.
Beda Punxgoaran dan SRF dengan band metal adalah kemampuan mereka menyuarakan keresahan dalam bahasa lokal yang akrab. Mereka punya single kuat sebelum membuat album, membangun fanbase loyal, dan hadir dalam format audio dan visual yang mudah dicerna. Mereka mengerti cara kerja distribusi karya.
Sedari awal SRF lebih tertutup. Mereka pernah bergabung dengan Siantar Hip Hop Soul (SHS), tapi keluar kemudian karena merasa manajemennya tidak terstruktur. Mereka memilih berdiri sendiri. Bagi mereka, komunitas tidak terlalu berpengaruh sebab karya yang berbicara. Tapi, mereka tetap ingin band ini diwariskan ke anak mereka sendiri, bukan ke personil baru.
Sementara Bloodnesia justru melihat pentingnya komunitas sebagai bagian dari regenerasi. Mereka menyebut bahwa tanpa dukungan komunitas, talenta muda tidak akan menemukan panggungnya. Namun keterbatasan ruang, fasilitas, dan koneksi membuat regenerasi musisi metal nyaris stagnan. Mereka merasa komunitas hanya kuat ketika ada tokoh sentral. Tanpa itu, band-band baru tenggelam dalam isolasi
Belajar dari Bandung
Musisi Siantar banyak yang menjadikan Bandung kiblat. Di balik gegap gempita musik Bandung, menurut mereka di sana tersembunyi sistem yang tidak dibangun dalam semalam. Ada pola keberpihakan, ruang ekspresi, dan regenerasi yang konsisten, yang membuat ibukota Jawa Barat ini bukan sekadar kota kreatif dalam slogan, tetapi dalam praktik. Setiap band baru mendapat ruang untuk tampil. Setiap komunitas diakui sebagai bagian dari ekosistem. Dan yang lebih penting, musik diperlakukan sebagai budaya, bukan sekadar hiburan.

Guido dari Punxgoaran pernah menyampaikan kritik tajam, bahwa pemerintah Pematangsiantar lebih memilih mengeluarkan ratusan juta untuk band nasional dalam perayaan ulang tahun kota, ketimbang membangun sistem keberlanjutan bagi musisi lokal. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, tapi cerminan betapa jauh jarak antara niat membangun dan keberpihakan nyata.
Bandung, sebagai kota yang kerap disebut barometer musik Indonesia, tidak lepas dari peran komunitas dan dukungan struktural. Ada ampiteater publik, panggung jalanan, kurasi acara berbasis lokalitas, dan jaringan distribusi yang membuka jalan bagi rilisan fisik dan digital secara seimbang. Band-band seperti Jasad, Burgerkill, hingga Mocca pernah memulai dari gigs kecil yang diberi tempat bukan dihalangi.
Sebaliknya, di Pematangsiantar, panggung-panggung seperti Lapangan Pariwisata, Taman Bunga, atau Adam Malik justru mati suri. Kerap bukan karena tak ada musisi yang siap tampil tapi karena regulasi dan pengelolaan yang membuat mereka tak bisa masuk. Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pernah menjadi momok, membungkam suara musik di ruang publik. Dan meski kini dicabut, trauma struktural itu masih menyisa. Ditambah lagi, akses ke panggung di Siantar kerap berbasis kedekatan personal, bukan pada kualitas atau karya.
Komunitas metal seperti Paku Mati pun menyebut bahwa regenerasi di Bandung berjalan karena senior memberi ruang dan warisan. Di Siantar, semuanya terpaku pada inisiatif individu. Ini bukan hanya soal semangat, tapi tentang ketimpangan sistem. Semangat saja tidak cukup jika tak ada ekosistem yang menopang.
Punxgoaran, SRF, Bloodnesia, dan Paku Mati membuktikan bahwa Pematangsiantar punya talenta, karya, bahkan fanatisme lokal yang layak dibanggakan. Namun semuanya berjalan nyaris tanpa sistem. Tidak ada kebijakan kota yang menjadikan musik sebagai bagian dari visi pembangunan kultural. Tidak ada program keberlanjutan yang memberi ruang belajar, promosi, distribusi, dan regenerasi secara simultan.

Sementara Bandung membangun ruang kreatif seperti Ruang Gelap, Potluck Creative Space, hingga Ujungberung Rebels, Siantar masih bermimpi tentang studio musik yang menyatu dengan kafe impian sederhana Guido yang hingga kini belum juga terwujud. Sebuah ampiteater pun belum pernah dibahas serius, padahal wahana itu bisa menjadi pusat pertunjukan dan edukasi seni.
Di Bandung, musik bukan hanya tentang bunyi tapi tentang hidup bersama. Juga, ihwal kota yang tumbuh bersama warganya, melalui karya; bukan hanya seremoni. Siantar, dengan sejarah musik dan keanekaragaman budaya seharusnya bisa lebih dari sekadar penonton.
Maka, jika Pematangsiantar ingin kembali hidup sebagai kota yang punya jiwa, perlu belajar dari Bandung: memberi ruang, bukan sekadar panggung. Memberi keberlanjutan, bukan sekadar hiburan sesaat. Dan yang paling penting, memberi kepercayaan kepada musisi lokal bukan karena mereka murah tapi karena mereka bagian dari wajah kota itu sendiri. Dengan kata lain, membangun ekosistem yang sehat. (Bersambung)
Penulis: Ris Taruli Aritonang, Amelia Wulandari Pardede, Triveni Gita Lestari Waloni, dan Michael Josua Robert Sijabat (peserta Sekolah Jurnalisme Parboaboa (SJP) Pematangsiantar, Batch 2. SJP merupakan buah kerja sama Parboaboa.com dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia).
Editor: P. Hasudungan Sirait